Memahami Radikalisme, Mencegah Terorisme
Pemerintah berupaya mencegah radikalisasi ini terutama bagi mereka yang berisiko mengalami kekerasan politik atau mungkin teroris....
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Terorisme telah menjadi perhatian kebijakan yang signifikan bagi beberapa negara Asia Tenggara, diantaranya Indonesia.
Setelah Bom Bali pada tahun 2002, Asia Tenggara dipandang oleh Amerika Serikat sebagai lapisan kedua dalam perang global melawan terorisme.
Sejak proklamasi tersebut pada tahun 2002, ancaman teror di Asia Tenggara telah meningkat secara eksponensial dan bersifat multidimensi.
Banyak serangan teroris telah dilakukan di Filipina, Thailand, dan Indonesia selama dua dekade terakhir.
Isu terorisme sendiri seringkali disandingkan dengan radikalisme yang dipandang sebagai akar tindakan kekerasan dan teror.
Pemerintah berupaya mencegah radikalisasi ini terutama bagi mereka yang berisiko mengalami kekerasan politik atau mungkin teroris.
Namun, menentukan strategi untuk melakukan hal ini akan bergantung pada definisi yang diambil mengenai radikalisme, karena hal ini akan menentukan bagaimana pemerintah memutuskan untuk mencegah radikalisasi dan mengatasi kekhawatiran yang ditimbulkan.
Mendefinisikan radikalisasi telah menjadi permasalahan dalam ilmu-ilmu sosial. Istilah ‘radikal’ berasal dari kata Latin radix (akar), dan radikalisasi secara harfiah berarti proses ‘kembali ke akar’.
• Terjun ke Dunia Politik, Intip Kesibukan Atlet Tinju Daud Jordan
Dalam kamus Oxford, radikalisme didefinisikan sebagai keyakinan atau tindakan orang-orang yang menganjurkan reformasi politik atau sosial secara menyeluruh.
Istilah ‘radikal’ sendiri sudah digunakan pada abad ke-18, dan sering dikaitkan dengan masa pencerahan serta revolusi Perancis dan Amerika pada periode tersebut.
Istilah ini menjadi luas pada abad ke-19 ketika istilah ini sering merujuk pada agenda politik yang menganjurkan reformasi sosial dan politik secara menyeluruh.
Dengan demikian, pada masa itu, radikalisme mengandung gagasan sekularisme, komponen pro-demokrasi, dan bahkan tuntutan kesetaraan seperti kewarganegaraan egaliter dan hak pilih universal.
Historisitas gagasan radikalisasi itu sendiri tampaknya terkait dengan kekhawatiran akan penolakan terhadap ancaman bagi status quo dan ideologi politik yang dapat membawa perubahan dalam bentuk apa pun.
• BPBD: Wilayah Kalbar Pagi Ini Bersih dari Titik Api
Plastisitas gagasan ini dikombinasikan dengan peran pembenaran yang dimainkannya terhadap sistem sehingga secara paradoks memberi kita lebih banyak informasi tentang karakteristik kelompok yang menggunakan gagasan ini dan apa target mereka.
Tidak ada konsensus yang muncul mengenai akar penyebab radikalisasi. Narasinya seringkali saling bersaing antara marginalisasi sosial-ekonomi dan politik di satu sisi dan motivasi ideologis di sisi lain.
Sayangnya, setelah peristiwa 9 September, istilah radikalisasi menjadi terkait dengan ‘perekrutan’ oleh para ekstremis, yang mencoba membujuk orang-orang yang marah untuk bergabung dalam perang (Coolsaet, 2019).
Masih kaburnya istilah radikalisme seringkali dinarasikan secara bergantian dengan ekstremisme, terorisme, dan fundamentalisme; sehingga seolah bermakna sama.
Radikalisme tentu saja berbeda dari yang lain, karena ia menyampaikan sebuah proses di mana individu yang melakukan radikalisasi mencoba menunjukkan penolakan dan kritik mereka terhadap dampak buruk dari status quo.
Inilah sebabnya mengapa akar penyebab radikalisasi harus dikaji lebih baik sebelum dicap sebagai sesuatu yang merusak seperti ekstremisme dan terorisme.
Analisis retrospektif Craig Calhoun terhadap istilah radikalisasi dalam kaitannya dengan gerakan sosial dapat membantu kita memahami akar penyebab radikalisasi saat ini dan membedakannya dari ekstremisme dan terorisme.
Berfokus pada gerakan sosial awal abad ke-19, Craig Calhoun (2011) membuat tiga klasifikasi radikalisme: radikalisme filosofis, radikalisme taktis, dan radikalisme reaksioner.
Radikalisme filosofis berkenaan dengan penembusan masalah masyarakat hingga ke akar-akarnya dengan analisis rasional dan program untuk memahami transformasi struktural ruang publik.
Radikalisme taktis yang dilakukan para aktivis terutama terkait dengan upaya mereka untuk
melakukan perubahan segera yang memerlukan penggunaan kekerasan dan tindakan ekstrem lainnya untuk mencapainya.
Radikalisme reaksioner yang dialami oleh mereka yang terkena dampak buruk modernisasi lebih merupakan upaya mereka untuk menyelamatkan apa yang mereka hargai dalam komunitas dan tradisi budaya akibat pertumbuhan kapitalisme.
Klasifikasi tersebut tidak saling eksklusif.
Mengikuti alur pemikiran ini, para pemimpin reformasi pada akhir orde baru dapat dianggap bersikap radikal, karena mereka mengklaim mengambil kembali apa yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam filsafat, banyak ilmuwan bersikap radikal dalam upayanya menganalisis pengetahuan dengan memikirkan kembali kondisi-kondisi dasarnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, ada juga individu radikal yang menantang tatanan hierarki dengan menilai hal-hal mendasar bagi dirinya sendiri, dipandu oleh cahaya batin, indera, dan akal ilahi.
Namun, berpikir radikal dan kemudian menyalahkan pihak lain oleh karena merasa superior, paling benar, paling hebat diantara lainnya bisa menjadi ekstrimisme.
Pikiran atau ide radikal ditambah dengan kekerasan merupakan tindakan terrorisme.
Dan kemudian menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membumikan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya sebagai tali pemersatu diantara keberagaman yang ada.
Penulis: Haryanto, SH., SIK., MA.
Mahasiswa Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian
| Timnas Putri Indonesia Vs Vietnam Live Perebutan Juara 3 Piala AFF U 16 Wanita 2025, Ini Linknya |

|
|---|
| Sejarah Hari Ini 30 Agustus Timor Timur Pisah dari Indonesia |

|
|---|
| 26 Agustus Hari Anjing Nasional, Dimana Peringatan National Dog Day ? |

|
|---|
| Film Horor SUKMA 2025, Teror Cermin Kuno yang Menghantui |

|
|---|
| Hasil Liga Asia Tenggara 2025 ASEAN Club Championship: Johor Darul Takzim JDT, Svey Rieng Sempurna |

|
|---|










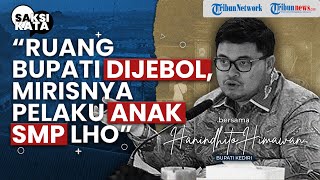





Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.