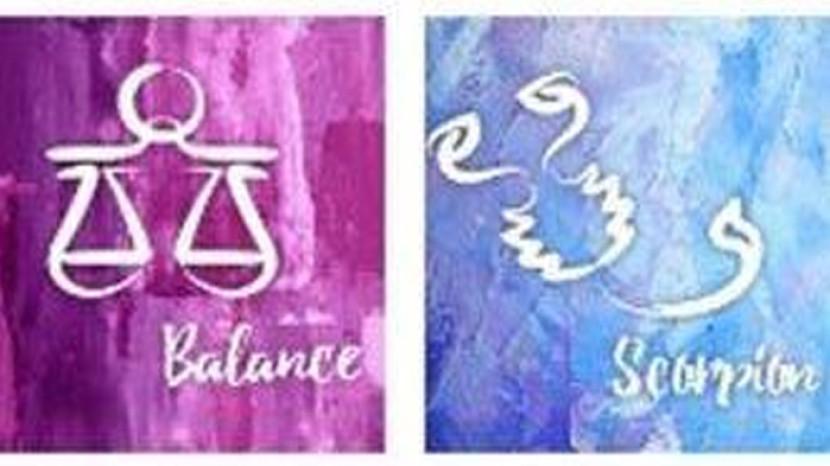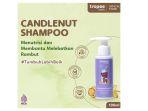Opini
Gawai dan Nasib Perladangan Manusia Dayak
Penyelenggaraan Gawai maupun sebutan lainnya melalui modifikasi di berbagai level justeru terkesan menafikkan keselarasan relasi antara harapan.
Oleh: Hendrikus Adam (1)
Musim gawai tiba dan semarak ucapan syukur masyarakat Dayak menggema di berbagai wilayah Kalbar khususnya. Pada sejumlah tempat ucapan syukur atas atas hasil pertanian padi bahkan telah usai dan ada pula yang baru akan segera dilaksanakan. Mengenang gawai kali ini, mengingatkan penulis pada pernyataan Bapak Adrianus Asia Sidot beberapa waktu lalu.
Tanggal 19 April 2015 pukul 17.52 Wib, Bupati Landak tersebut melalui akun facebook pribadinya menyampaikan pesan tidak biasa mengenai penyelenggaraan jelang pesta syukur panan padi (Gawai) masyarakat Dayak Kanayatn yakni Naik Dango. Status di facebook tersebut direspon beragam oleh sejumlah pengguna jejaring sosial. Umumnya memberi dukungan secara moral atas pernyataan beliau. Melalui jejaring akun facebook dengan nama Adrianus Asia Sidot, beliau menyampaikan pernyataan sebagai berikut;
"Saya berusaha agar Naik Dango XXX tahun 2015 di Ngabang menjadi Naik Dango yang bermartabat dan mengembalikan kemurnian Budaya Dayak. Tak Peduli dengan ancaman para preman yang mengatasnamakan budaya Dayak, yang memelihara judi, miras, narkoba dan prostitusi yang berkedok Jonggan. Saya takkan gentar menghadapi mereka sekalipun hanya saya sendiri."
Secara langsung, pernyataan Adrianus Asia Sidot menyiratkan sejumlah pesan gamblang dan hal ini dapat dipahami. Beliau misalnya berkeinginan agar Naik Dango yang akan digelar tidak sekadar mengatasnamakan budaya Dayak yang diwarnai dengan perjudian, miras, narkoba dan hiburan yang tidak sehat (berkedok jonggan). Selain itu, pernyataan Adrianus Asia Sidot menyiratkan kesan adanya "ancaman" dari sejumlah oknum yang tidak sejalan dengan keinginan beliau.
Secara singkat, dalam bahasa yang sederhana melalui pernyataan tersebut, Adrianus Asia Sidot ingin menyampaikan bahwa judi, miras, narkoba dan hiburan tidak sehat di ajang Gawai Naik Dango yang selama ini bukan warna asli dari kehidupan manusia Dayak.
Dengan kata lain, pernyataan beliau mengkonfirmasi bahwa perjudian, miras, narkoba dan hiburan tidak sehat lainnya bukan bagian dari budaya Dayak. Jadi pengembalian kemurnian budaya bermartabat menurut beliau yang kini menjabat sebagai Bupati Landak dapat dipahami sebagai usaha "memurnikan" agar persepsi tentang gawai tidak cenderung negatif.
Apa yang disampaikan beliau tentu sangat logis sehingga layak diapresiasi. Terlebih selama ini, tidak banyak pihak yang cukup berani bersuara lantang terkait dengan sejumlah fenomena "menyimpang" yang masih kerap menghiasi acara gawai sebagaimana dimaksud.
Dengan demikian, kemurnian Budaya Dayak melalui Gawai Naik Dango bermartabat sebagaimana tersirat dalam pernyataan Adrianus Asia Sidot adalah Naik Dango yang (diharapkan) bebas dari keempat hal yakni perjudian, miras, narkoba dan hiburan lainnya yang menyimpang dari adat kebiasaan manusia Dayak. Tentu pernyataan keinginan memurnikan budaya hanya akan bermakna dan berbuah bila disertai komitmen tindakan, bukan pernyataan politis semata. Hemat penulis, tentu saja apa yang diucapkan Adrianus Asia Sidot serius. Semoga pula konsisten.
Dengan semangat seperti yang dicita-citakan Adrianus Asia Sidot dimaksud, maka pantas menjadi refleksi kita bersama; sudahkah gawai yang dilaksanakan selama ini terbebas dari sejumlah bentuk kegiatan maupun berbagai hiburan tidak sehat? Selain itu, sudahkah hakikat pesta syukur atas hasil pertanian padi pada masa kini sungguh selaras dengan dasar filosofis Gawai Manusia Dayak sejati?
Memaknai Gawai
Ada beragam sebutan khusus tentang pesta syukur atas panen padi pada komunitas masyarakat Dayak. Naik Dango misalnya, dari sisi istilah berakar dari bahasa Dayak Kanayatn yakni naik/menaiki sebuah dango (pondok) untuk menyimpan hasil pertanian ladang (padi) bagi masyarakat Dayak.
Komunitas masyarakat Dayak biasanya menyimpan hasil panen berupa padi dan sembari menanti waktu untuk mengawali pertanian baru maka digelarlah ritual adat guna memanjatkan doa agar hasil panen menjadi berkat bagi semua. Pada momentum upacara ritual adat Naik Dango, masyarakat Dayak mengadakan doa syukur, makan bersama dan saling mengunjungi antar sanak saudara. Naik Dango dalam tradisi masyarakat Dayak menyiratkan relasi dan jalinan silaturahmi antar sesama. Karenanya selain sebagai bentuk syukur dan mohon restu kepada Tuhan, juga sebagai pertanda penutupan tahun peladangan dan penguat hubungan persaudaraan (solidaritas).
Naik Dango biasanya diselenggarakan pada saat usai masa panen padi dan atau sebelum memulai pertanian ladang baru. Karenanya peristiwa ini juga sebagai pertanda awal dan akhir siklus pertanian ladang. Naik Dango dalam hal ini umumnya dimaknai sebagai pesta ungkapan syukur masyarakat Dayak kepada Sang Pencipta atas hasil pertanian padi ladang yang melimpah, sekaligus menggambarkan suatu harapan agar panen berikutnya juga lebih baik.
Dari sisi historis, pesta panen padi dan sejenisnya bagi komunitas masyarakat Dayak telah lama dilakukan dengan berbagai sebutan seperti naik dango, roah, ngabayotn, nyamaru, Nyelepat Taun, gawai nosu minu podi, dan lain sebagainya. Pelaksanaan ucapan syukur tersebut dilakukan selaras dengan kegiatan berladang yang masih hidup dan biasanya ditandai dengan tersedianya lahan yang memadai untuk pertanian ladang komunitas kala itu.
Namun demikian, dalam perjalanannya, kini perayaan ucapan syukur tersebut terus diberkembang dengan "modifikasi" modern serta dikembangkan dalam lingkup yang luas (luar komunitas) pada berbagai level wilayah tingkat kecamatan dan kabupaten, juga propinsi. Pada tingkat provinsi dikenal dengan sebutan umum Gawai dan dalam perkembangannya dikenal dengan Pekan Gawai Dayak (Pada tahun 2015, beberapa waktu lalu sudah digelar di Rumah Radakng). Modifikasi atas gawai tersebut bila dicermati lebih berfokus pada upaya apresiasi potensi sumberdaya dan pelestarian seni maupun budaya semata. Dalam kemasan modern yang dimodifikasi tersebut, pesta Gawai (dalam hal ini Naik Dango) sendiri mulai dilakukan sejak tahun 1986, sekitar 30 tahun lalu.
Penyelenggaraan Gawai maupun sebutan lainnya melalui modifikasi di berbagai level dimaksud justeru terkesan menafikkan keselarasan relasi antara harapan dan realita. Pada satu sisi gawai seperti halnya Naik Dango dan atau sebutan lainnya diamini sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen pertanian padi (ladang), namun pada sisi lain realitasnya harus diakui bahwa komunitas masyarakat Dayak yang menggeluti kegiatan berladang telah mengalami "persoalan" terkait ketersediaan lahan pertanian yang terus "terdegradasi". Bahkan di sejumlah komunitas, ada diantaranya yang tidak lagi dapat bertani ladang karena lahan yang mereka miliki tidak memungkinkan lagi dikelola oleh karena berbagai faktor.
Satu di antaranya dikarenakan massifnya ekspansi industri ekstraktif (perkebunan, hutan tanaman, pertambangan) melalui izin pemerintah pada sejumlah wilayah kelola dan sumber kehidupan komunitas masyarakat Dayak. Selain berdampak langsung bagi terjadinya deforestasi dan degradasi terhadap ekosistem, kebijakan pembangunan yang kerap disertai janji memberi kesejahteraan masyarakat tersebut seringkali menempatkan komunitas hanya sebagai objek semata yang selanjutnya berdampak pada multi aspek. Satu diantara akibatnya, terjadi krisis lahan pertanian pangan untuk berladang sebagaimana yang dialami sejumlah komunitas, penyerobotan tanah hingga kriminalisasi menghiasi dinamika tata kelola sumberdaya alam di tanah sekitar wilayah masyarakat lokal.
Ruang Refleksi Bersama
Perayaan gawai dan atau dalam istilah lainnya yang masih terus dirayakan masyarakat Dayak saat ini sejatinya dapat dijadikan peluang baik untuk berbenah. Ruang di mana penting kiranya menyelaraskan makna gawai sebagai bagian dari harapan ideal dengan kenyataan masa kini.
Pesta syukur melalui gawai tersebut juga sedianya dijadikan ruang untuk memastikan komitmen bersama dalam menjaga maupun melindungi keberlanjutan kegiatan pertanian ladang yang menjadi bagian penting dari eksistensi, identitas, dan siklus kehidupan manusia Dayak. Pada sisi lain, peran pemerintah untuk memastikan kelangsungan siklus pertanian ladang yang menjadi sentral dari keberadaan manusia Dayak menjadi keharusan, mutlak ada.
Upaya menjaga keberlanjutan pertanian ladang berarti pula bagaimana memastikan jaminan perlindungan, penghormatan dan penegakkan hak-hak masyarakat atas sumberdaya lahan maupun sumber kehidupan lainnya. Pada perhelatan gawai padi, maka dukungan berbagai pihak utamanya pemerintah sangat diharapkan tidak sekedar ketika acara seremonial gawai dilangsungkan. Namun penting kiranya memastikan agar kelangsungan hak hidup komunitas atas tanah sebagai sumber kehidupan tetap dijamin.
Bila tanpa ada jaminan dan perlindungan hak atas tanah dan sumber kehidupan komunitas, maka jelas perlahan namun pasti lahan pertanian untuk berladang bagi masyarakat Dayak akan terus menyusut. Hal ini berarti pula sebagai lonceng kematian pada keberlanjutan kegiatan perladangan manusia Dayak.
Sebelum sungguh-sungguh terlambat, maka kebijakan alih fungsi tanah dan lahan dalam wilayah kelola komunitas yang menjadi potensi ancaman serius atas keberadaan petani ladang hendaknya sungguh memperhatikan keselamatan komunitas dan lingkungannya.
Hakikat perayaan gawai sejati sebagai ungkapan syukur yang selaras dengan spirit asalnya penting menjadi semangat bersama generasi manusia Dayak saat ini. Tentu pantas disampaikan apresiasi kepada komunitas yang masih menyelenggarakan gawai namun tetap dapat melakukan perladangan. Dengan demikian masih seiring antara harapan dan kenyataan.
Sebab bila realitanya petani ladang di sejumlah komunitas tidak lagi dapat berladang dan otomatis tidak dapat menghasilkan padi dari berladang, maka gawai yang dipromosikan melalui tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi bahkan pula di tingkat wilayah Desa sekalipun, akan tetap terasa "gersang". Ibarat raga tanpa jiwa.
Gawai sebagai ruang apresiasi potensi sumberdaya dan pelestarian seni maupun budaya penting direkonstruksi kembali dengan menambahkan penegasan komitmen bersama untuk memurnikan martabat dan budaya Dayak sebagaimana harapan Adrianus Asia Sidot. Lebih dari itu, menjadi sangat penting pula menambahkan adanya jaminan kepastian akses manusia Dayak terhadap tanah, sumber kehidupan untuk kelangsungan perladangan melalui kebijakan pemerintah.
Nasib perladangan manusia Dayak akan sangat ditentukan oleh keberadaan tanah berikut sumber daya produktif lainnya seperti hutan dan air dalam wilayah kelola mereka. Tanah menjadi sumber hidup dan kehidupan yang tidak cukup dilihat sebagai komoditas, namun memiliki nilai begi komunitas. Tanah penting untuk kelangsungan perladangan padi. Sebab, hanya padi dari kegiatan pertanian (ladang) yang dapat menjadi sarana perhelatan gawai. Bukan biji kelapa sawit dan bukan juga jenis biji atau buah lainnya. Tanpa tanah, tidak ada pertanian ladang. Dan bila tanpa padi, gawai tamat!!! Selamat menyelenggarakan dan memaknai gawai ***.
[1] Penulis, aktif di WALHI Kalimantan Barat. Peminat isu Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Perdamaian, sosial budaya dan Masyarakat Adat.